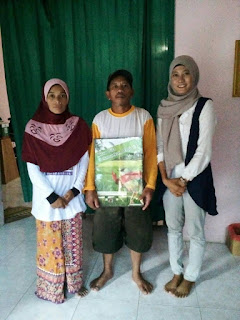Jumlah populasi di dunia ini dari
tahun ke tahun akan semakin bertambah dan jenis kebutuhan manusia akan
meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah populasi di dunia. Hal ini juga
terjadi pada kebutuhan akan energi semakin meningkat sehingga persediaan energi
khususnya energi yang tidak dapat diperbaharui semakin berkurang
pula kuantitasnya, bahkan lama-kelamaan akan habis. Hal
ini dapat
dilihat dari jumlah konsumsi BBM Indonesia terus meningkat. Saat ini, hampir
80% kebutuhan energi dunia dipenuhi oleh bahan bakar fosil. Padahal, penggunaan
bahan bahar fosil bisa mengakibatkan pemanasan global.
Untuk mengurangi ketergantungan pada
bahan bakar fosil (minyak/gas, bumi, dan batu bara) sebagai sumber energi yang
tidak terbarukan, tentu akan mencari sumber-sumber energi lainnya yang akan
digunakan sebagai bahan bakar alternatif atau pengganti asalkan potensi sumber
dayanya mudah diperoleh secara lokal supaya harganya lebih murah dan
terjangkau.
Biodiesel adalah salah satu bahan
bakar alternatif yang ramah lingkungan dan tidak beracun. Sehingga, lebih
aman jika disimpan dan digunakan serta tidak mempunyai efek terhadap kesehatan
yang dapat dipakai sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Biodiesel yang
berasal dari minyak nabati dikenal sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui
karena umumnya dapat diekstrak dari berbagai hasil produk pertanian dan
perkebunan. Bahan baku yang berpotensi sebagai bahan baku pembuat
biodiesel antara lain kelapa sawit, kedelai, jarak pagar, alpukat, dan beberapa
jenis tumbuhan lainnya (Martini 2005).
Salah satu sumber bahan baku
biodiesel adalah buah alpukat. Bagian dari buah alpukat yang dapat digunakan sebagai
biodiesel adalah bijinya, melalui esterifikasi dan/transesterifikasi dengan
alkohol serta bantuan katalis. Untuk mengetahui kelayakan minyak biji
alpukat sebagai bahan baku biodiesel, maka perlu dilakukan beberapa pengujian
untuk mengetahui angka asam, asam lemak bebas, densitas minyak, viskositas, dan
yield.
Salah satu alasan mengapa
menggunakan biji alpukat dibandingkan dengan tanaman lainnya dikarenakan buah
alpukat banyak terdapat di lingkungan masyarakat yang bijinya belum
dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, yang paling penting yaitu kandungan
minyak biji alpukat lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman-tanaman seperti
kedelai, jarak, biji bunga matahari, dan kacang tanah. Pemilihan biji alpukat
sebagai salah satu sumber minyak nabati karena kandungan minyaknya relatif
tinggi dibandingkan tanaman lain yaitu sekitar 2638 liter/ha dalam 2217 kg/ha.
Sedangkan tanaman seperti jarak adalah 1892 liter/ha dalam 1590 kg/ha dan bunga
matahari 925 liter/ha dalam 800 kg/ha. Selain itu, bahan bakar ini lebih
ekonomis dan ramah lingkungan karena kadar belerang dalam minyak tersebut
kurang dari 15 ppm, sehingga pembakaran berlangsung sempurna dengan dampak
emisi CO, CO2 serta polusi udara yang rendah (Sofia 2006).
Beragam penelitian mendukung
penggunaan minyak biji alpukat sebagai biodiesel. The National Biodiesel Foundation
(NBF) telah meneliti buah alpukat sebagai bahan bakar sejak 1994. Joe Jobe
selaku direktur eksekutif NBF mengungkapkan bahwa biji alpukat mengandung lemak
nabati yang tersusun dari senyawa alkil ester. Bahan ester itu memiliki
komposisi yang sama dengan bahan bakar diesel, bahkan lebih baik dibandingkan
solar sehingga gas buangnya lebih ramah lingkungan. Pemanfaatan biji alpukat
sampai sekarang hanya digunakan sebagai obat penghilang stress saja dan belum
dimanfaatkan untuk yang lainnya padahal biji alpukat memiliki kandungan fatty
acid methyl ester sebagai bahan pembuat biodiesel. (Hidayat 2008)
Biodiesel dibuat melalui suatu
proses kimia yang disebut transesterifikasi dimana gliserin dipisahkan dari
minyak nabati. Proses ini menghasilkan dua produk yaitu metil esters
(biodiesel)/mono-alkyl esters dan gliserin yang merupakan produk samping. Bahan
baku utama untuk pembuatan biodiesel ini adalah minyak biji alpukat.
Sedangkan sebagai bahan baku penunjang yaitu alkohol. Pada pembuatan biodiesel
dibutuhkan katalis untuk proses esterifikasi, katalis dibutuhkan karena alkohol
larut dalam minyak. Alkohol yang digunakan sebagai pereaksi untuk minyak nabati
adalah methanol, namun dapat pula digunakan ethanol, isopropanol atau butyl,
tetapi perlu diperhatikan juga kandungan air dalam alkohol tersebut. Bila
kandungan air tinggi akan mempengaruhi hasil biodiesel yang kualitasnya rendah,
karena kandungan sabun, ALB dan trigliserida tinggi. Disamping itu, hasil
biodiesel juga dipengaruhi oleh tingginya suhu operasi proses produksi, lamanya
waktu pencampuran atau kecepatan pencampuran alkohol.
Katalisator dibutuhkan pula guna
meningkatkan daya larut pada saat reaksi berlangsung. Pada umumnya produksi
biodiesel dilakukan menggunakan katalis homogen yaitu KOH atau NaOH yang
memiliki beberapa kelemahan yaitu tidak dapat digunakan kembali. Selain itu
dapat menghasilkan reaksi samping yang tidak diharapkan (saponifikasi),
pemisahan antara katalis dan produk harus melalui berbagai tahapan sehingga
meningkatkan biaya produksi. Pada katalis heterogen seperti: CaO, MgO, dan CaCO3 kelemahan
diatas dapat dicegah karena katalis-katalis ini berbentuk padat, sehingga mudah
dipisahkan dan dapat diperoleh kembali (recovery) melalui dekantasi dan
filtrasi menggunakan alat yang sederhana. Dengan demikian dapat menghemat biaya
produksi dan diharapkanyield yang dihasilkan lebih tinggi
dibandingkan menggunakan katalis homogen. Katalis yang akan dipilih tergantung
minyak nabati yang digunakan, apabila digunakan minyak mentah dengan kandungan
ALB kurang dari 2%, disamping terbentuk sabun dan juga gliserin. Katalis
tersebut pada umumnya sangat higroskopis dan bereaksi membentuk larutan kimia
yang akan dihancurkan oleh reaktan alkohol.
Bahan baku yang digunakan pada
pembuatan biodiesel ini yaitu biji alpukat. Biji alpukat dikeringkan pada suhu
±110ºC selama ±60 menit. Kemudian diekstraksi menggunakan pelarut n-heksana
pada suhu 65ºC sebanyak 5 siklus. Selanjutnya larutan ekstrak dievaporasi pada
suhu 40ºC dalam keadaan vakum. Pemurnian minyak dilakukan dengan cara degumming menggunakan
H3PO4 0,8%, sedangkan pemisahan gum menggunakan
sentrifuga 2500 rpm. Ekstraksi ini dilakukan menggunakan sokhlet dengan
suhu operasi 65ºC. Untuk memisahkan minyak dari pelarutnya dilakukan evaporasi
secara vakum pada suhu 40ºC.
Pemurnian dilakukan dengan
menggunakan metode degumming. Metode ini bertujuan untuk
menghilangkan pengotor seperti getah atau lendir yang terdiri dari fosfatida,
protein, karbohidrat, dan air tetapi tidak menghilangkan asam lemak bebas (FFA)
yang terdapat pada minyak biji alpukat (Mittlebach 2004). Sentrifugasi
dilakukan untuk memisahkan antara getah (gum) dengan minyak.
Tahap berikutnya adalah penelitian
utama, yaitu pembuatan metil ester (biodiesel) dari minyak biji alpukat melalui
transesterifikasi pada suhu 60ºC selama 1 jam. Dalam percobaan ini kalsium
metoksida direaksikan dengan minyak biji alpukat murni. Kalsium metoksida
dibuat dengan cara mereaksikan antara metanol dengan kalsium oksida (CaO).
Jumlah CaO yang digunakan adalah 2% dan 6%/b-minyak, sedangkan perbandingan mol
antara minyak dengan metanol yang digunakan adalah 1:6.
Kelebihan penggunaan katalis
heterogen dibandingkan dengan katalis homogennya ialah bahwa pemisahan katalis
heterogen lebih mudah dan dapat digunakan kembali. Dalam penelitian ini hal
tersebut di atas sudah tercapai dengan terbentuknya tiga fasa yaitu lapisan
atas adalah biodiesel, tengah gliserol dan bawah CaO. Dengan demikian CaO dapat
digunakan kembali (recovery CaO).
Hasil analisis sifat fisika dan
kimia biodiesel menggunakan variasi konsentrasi katalis CaO (%-b) dapat
diperoleh nilai angka asam dan %FFA, CaO 6% b-minyak memiliki nilai yang lebih
rendah dibandingkan dengan CaO 2% b-minyak. Sehingga pada penggunaan CaO 6%
b-minyak menghasilkan biodiesel yang memiliki karakteristik mendekati SNI.
Penentuan sifat fisika dan kimia
biodiesel tidak seluruhnya dilakukan sesuai dengan penentuan yang tertera pada Syarat
Mutu Biodiesel. Yang diuji hanya sifat fisika dan kimia biodiesel yang mewakili
(representatif) penggunaannya di mesin yaitu viskositas, massa jenis, pH, kadar
air, %FFA, dan angka asam.
Biodiesel mengandung metil ester
sebesar 48,02%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua minyak biji alpukat dapat
dikonversi menjadi metil ester. Penyebab rendahnya jumlah metil ester masih
adanya kandungan air dalam minyak saat transesterifikasi, sehingga pembentukan
senyawa metoksida belum sempurna. Bila ditinjau dari komposisi asam lemak jenuh
dan tak jenuhnya, biodiesel hasil penelitian mengandung 38,87% asam lemak tak
jenuh dan 9,15% asam lemak jenuh. Hal ini sesuai dengan literatur yang
menyatakan bahwa minyak nabati yang dapat diolah menjadi biodiesel harus memiliki
kandungan asam lemak tak jenuh yang tinggi karena dapat mencegah terbentuknya
padatan yang akan menghambat kinerja mesin. Berdasarkan hasil analisis fisika
dan kimia menunjukkan bahwa minyak biji alpukat layak digunakan sebagai bahan
baku pembuatan biodiesel, namun belum mencapai perolehan yang optimum.
Biodiesel dari minyak biji alpukat
diperoleh dengan proses transesterifikasi. Penggunaan katalis heterogen kalsium
oksida (CaO) dalam transesterifikasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
karakteristik biodiesel yang dihasilkan, sedangkan kelebihannya dapat digunakan
kembali karena pemisahannya lebih mudah. Berdasarkan sifat kimia dan fisikanya
minyak biji alpukat (Persea gratissima) dapat dimanfaatkan sebagai bahan
baku pembuatan biodiesel.
Sumber
:
Nama/
NIM : Amrina Rosyada/ 15/378267/PN/14073
Sumber:Google.com
Praktik budidaya tanaman yang pada
masa kini nasih dominan digunakan adalah cara konvensional dimana petani masih
menggunakan berbagai zat kimia yang berbahaya bagi lingkungan untuk melakukan
kegiatan bududaya tanaman. Salah satu dari kegiatan pada budidaya tanaman
adalah mengendalikan hama sert penyakit yang berpeluag besar menggagalkan hasil
budidaya tanaman menjadi optimal. Pada umumnya petani masih mengandalkan
pestisida untuk mengamankan hasil panennya dari berbagai serangan organisme
pengganggu tanaman (OPT). penggunaan pestisida sendiri pada prakiknya masih
terdapat berbagai permasalahan bagi beberapa aspek seperti kesehatan,ekonomi,social,serta
lingkungan.
Permasalahan yang ditimbulkan dari
penggunaan pestisida pada budidaya tanaman merupakan timbal balik yang timbul
akibat berbagai yang dilakukan petani di lapangan. Praktik-praktik tersebut
diantaranya adalah penyemprotan pestisida dengan volume sangat tinggi. Pencampuran
larutan yang digunakan pestisida secara sembarangan serta frekuensi
penyemprotan pestisida yang terlalu sering dan tidak menuruti jadwal
penyemprotan yang dianjurkan. terlebih pada saat penyemprotan pestisida, petani
tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) yang standar. Hal tersebut hanya
semakin memperburuk keadaan yang ditimbulkan dari penggunaan pestisida. Apabila
permasalahan-permasalahan tersebut merupakan fakta, maka pertanian di Indonesia
ini memiliki status darurat pestisida. Hasil yang diperoleh dari budidaya
tanaman tersebut tidak aman untuk dikonsumsi, lingkungan hidup menjadi
tercemari akibat residu pestidida yang berlebihan, serta kesehatan para petani
pun juga menjadi tercemar terlebih tidak tersedia asuransi.
Berbagai permaslahan yang timbul
akibat penggunaan pestisida secara semabarangan tentunya akan semakin pelik
apabila tidak ditangani oleh pihak yang berwanang, dalam hal ini adalah
pemerintah. Pemerintahan telah penerapan pengelolaan hama secara terpadu (PHT)
untuk mengendalikan organisme penggangu tanaman. PHT juga dapat memperkecil
dampak kerusakan tanaman serta menyelamatkan hasil bududaya tanaman. Pada prinsipnya,
penerapan PHT tidaklah serupa dengan pertanian konvensional dalam perlindungan
tanaman, namun secara praktiknyatidak jauh berbeda. Hal tersebut dapat
dijelaskan dengan penggunaan pestisida itu sendiri. Apabila pada PHT penggunaan
pestisida tetap digunakan untuk solusi yang terakhir dalam melakukan
perlindunagn tanaman.
Penggunaan pestisida pada sebuah
komoditas yang frekuensi yang tinggi tentu akan berdampak buruk bagi tanaman. Selain
membuat tanaman menjadi memiliki kandungan residu pestisida yang tinggi
penggunaan pestisida yang berlebihan juga membuat hama menjadi resisten
sehingga dengan cara bagaimanapun akan sulit untuk menekan populasinya. Saya berpendapat
bahwa penggunan pestisida masihlah krusial bagi kebijakan perlindungan tanaman,
namun perlu dicatat bahwa masih tersedia opsi lain yang mungkin masih dapat
diambil selain menggunakan pestisida untuk pertanian yang lebih sehat.
Daftar
Pustaka
Soetikno, S dan
Sastroutomo.1992 Pestisida dasar-dasar dan dampak penggunaannya. P.T. Gramedia
Jakarta.
Rifqi Huli Fahmi
15/383455/PN/14286
Fitri
Lusiana Kurniasari
(15/383530/PN/14361)
EKSTENSIFIKASI
LAHAN KERING UNTUK MENDUKUNG PERWUJUDAN SWASEMBADA PANGAN
Produksi pangan yang dihasilkan dari pertanian Indonesia
belum dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia sendiri. Indonesia
yang dikenal sebagai negara agraris dan maritime seharusnya dapat menghasilkan
produksi yang optimal dibidang pertanian dan perikanan. Dengan lahan pertanian
yang melimpah dan wilayah perairan yang luas, seharusnya Indonesia dapat
menjadi negara mengekspor pangan yang hebat. Namun, faktanya untuk memenuhi
kebutuhan pangan di wilayahnya sendiri, Indonesia masih mengandalkan impor
produk dan bahan pangan dari negara lain. Kondisi pangan di Indonesia masih
jauh untuk mencapai swasembada, bahkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor.
Meskipun demikian, menurut Prof. Dr. Dw idjono Hadi
Darwanto (2016), beberapa wilayah di Indonesia, seperti Sulawesi selatan
berhasil melaksanakan ekspor beras kurang lebih 1,5 juta ton per tahun. Hal
tersebut dapat terjadi karena Sulawesi selatan dapat memanfaatkan bibit padi
yang cocok untuk di tanam di wilayahnya dan dapat memanfaatkan lahan dengan
efisien. Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia mempunyai
kemampuan dengan sarana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama di
wilayah Indonesia itu sendiri.
Salah satu penyebab utama produksi pangan yang belum
optimal adalah pemanfaatan lahan yang kurang efektif. Selama ini, penggunaan
lahan untuk komoditas padi dan palawija dilaksanakan secara bergantian. Hal ini
tentu akan menekan jumlah produksi komoditas pangan tersebut. Apabila lahan
yang digunakan untuk melaksanakan budidaya komoditas tersebut dapat dipisahkan,
tentunya dapat meningkatkan jumlah produksi pangan yang dihasilkan. Ekstensifikasi
pertanian merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut. Ekstensifikasi pertanian adalah melakukan perluasan
lahan pertanian dengan memanfaatkan lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan
untuk usaha pertanian, misalnya dengan pembukaan lahan kering, lahan gambut,
dan hutan.
Pemanfaatan lahan kering untuk pertanian sering diabaikan
oleh para pengambil kebijakan, yang lebih tertarik pada peningkatan produksi
beras pada lahan sawah. Hal ini mungkin karena ada anggapan bahwa meningkatkan produksi padi sawah lebih mudah
dan lebih menjanjikan dibanding padi gogo yang memiliki risiko kegagalan lebih
tinggi. Padahal lahan kering tersedia cukup luas dan berpotensi untuk menghasilkan
padi gogo > 5 t/ha. Lahan kering yang potensial dapat menghasilkan bahan
pangan yang cukup dan bervariasi, tidak hanya padi gogo tetapi juga bahan
pangan lainnya, bila dikelola dengan menggunakan teknologi yang efektif dan
strategi pengembangan yang tepat. Bahan pangan bukan hanya beras, t e t
api juga j agung,
sorgum, kede l a i , kacang
hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan sebagainya, yang kesemuanya dapat dibudidayakan
di lahan kering (Abdurrahman, 2008)
.
Lahan ke r ing me rupakan
salah satu agroekosistem yang
mempunyai potensi besar untuk usaha pertanian, baik tanaman pangan,
hortikultura (sayuran dan buahbuahan) maupun tanaman tahunan dan peternakan.
Berdasarkan Atlas Arahan Tata Ruang Pertanian Indonesia skala 1:1.000.000
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat 2001), Indonesia
memiliki daratan sekitar 188,20 juta ha, terdiri atas 148 juta ha lahan kering
(78%) dan 40,20 juta ha lahan basah (22%). Tidak semua lahan kering sesuai
untuk pertanian, terutama karena adanya faktor pembatas tanah seperti lereng yang sangat curam atau
solum tanah dangkal dan berbatu, atau termasuk kawasan hutan. Dari total luas
148 juta ha, lahan kering yang sesuai
untuk budi daya pertanian hanya sekitar 76,22 juta ha (52%), sebagian besar
terdapat di dataran rendah (70,71 juta ha atau 93%) dan sisanya di dataran
tinggi. Di wilayah dataran rendah, lahan datarbergelombang (lereng < 15%)
yang sesuai untuk pertanian tanaman pangan mencakup 23,26 juta ha. Lahan dengan
lereng 15−30% lebih sesuai untuk tanaman tahunan (47,45 juta ha). Di dataran tinggi,
lahan yang sesuai untuk tanaman pangan
hanya sekitar 2,07 juta ha, dan untuk tanaman tahunan 3,44 juta ha (Abdurrachman,
2008).
Ekstensifikasi pertanian dengan memanfaatkan lahan kering
tentu akan menambah hasil produksi pangan yang dihasilkan. Hal tersebut dapat
terjadi karena wilayah yang digunakan untuk penanaman komoditas pangan, seperti
padi dan palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, dan lain-lain) semakin luas.
Pelaksanaan tersebut misalnya dapat dilaksanakan pemisahan lahan antara penanaman
padi dan palawija, yaitu dengan menanam palawija pada lahan kering, sedangkan
padi pada lahan basah yang umumnya digunakan untuk menanam padi. Hal tersebut sesuai dengan ilmu yang
dipelajari dalam budidaya pertanian, bahwa tanaman palawija merupakan tanaman
yang cocok ditanam pada lahan dengan ketersediaan air kapasitas lapangan, bukan
seperti padi yang membutuhkan air yang melimpah. Dalam pemanfaatan lahan kering
dapat dilakukan berbagai teknik atau metode irigasi agar ketersediaan air dapat
mencapai kapasitas lapangan. Misalnya dengan membuat bendungan khusus untuk
dialirkan pada lahan tersebut, mengolah tanah dengan pemberian pupuk yang
tepat, penyediaan mulsa organic untuk menjaga ketersediaan air dan menekan
evaporasi.
Menurut Abduachman (2008), pemanfaatan lahan kering dalam
usaha pertanian juga mengalami berbagai kendala Permasalahan dalam pengelolaan
lahan kering bervariasi pada setiap wilayah, baik aspek teknis maupun
sosial-ekonomis. Namun, dengan strategi dan teknologi yang tepat, berbagai masalah
tersebut dapat diatasi.
1.
Kesuburan tanah
Pada
umumnya lahan kering memiliki tingkat kesuburan tanah yang rendah, terutama
pada tanah-tanah yang tererosi, sehingga lapisan olah tanah menjadi tipis dan
kadar bahan organik rendah. Kondisi ini makin diperburuk dengan terbatasnya
penggunaan pupuk organik, terutama pada tanaman pangan semusim. Di samping itu, secara alami kadar bahan
organik tanah di daerah tropis cepat menurun, mencapai 30−60% dalam waktu 10
tahun (Brown dan Lugo 1990 dalam
Suriadikarta et al. 2002).
Bahan
organic memiliki peran penting dalam memperbaiki sifat kimia, fisik, dan
biologi tanah. Meskipun kontribusi unsur hara dari bahan organik tanah relative
rendah, peranannya cukup penting karena selain unsur NPK, bahan organik juga
merupakan sumber unsur esensial lain seperti C, Zn, Cu, Mo, Ca, Mg, dan Si
(Suriadikarta et al. 2002).
Hal
lain yang perlu diperhatikan adalah adanya tanah masam, yang dicirikan oleh pH
rendah (< 5,50), kadar Al tinggi, fiksasi P tinggi, kandungan basa-basa dapat
tukar dan KTK rendah, kandungan besi dan mangan mendekati batas meracuni
tanaman, peka erosi, dan miskin unsur biotik (Adiningsih dan Sudjadi 1993;
Soepardi 2001).
Dari
luas total lahan kering Indonesia sekitar 148 juta ha, 102,80 juta ha (69,46%)
merupakan tanah masam (Mulyani et al.
2004). Tanah tersebut didominasi oleh Inceptisols, Ultisols, dan Oxisols, dan
sebagian besar terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Lahan
kering masam di wilayah berbukit dan bergunung cukup luas, mencapai 53,50 juta
ha atau 52% dari total tanah masam di Indonesia. Tanah masam t e r s ebut umumnya
kur ang pot ens i a l untuk pertanian tanaman pangan karena tingkat
kesuburannya rendah, lereng
curam,
dan solum dangkal.
2.
Topografi
Di
Indonesia, lahan kering sebagian besar terdapat di wilayah bergunung (> 30%)
dan berbukit (15−30%), dengan luas masing-masing 51,30 juta ha dan 36,90 juta
ha (Hidayat dan Mulyani 2002). Lahan kering berlereng curam sangat peka terhadap
erosi, terutama bila diusahakan untuk tanaman pangan semusim dan curah hujannya
tinggi. Lahan semacam ini lebih sesuai untuk tanaman tahunan, namun
kenyataannya banyak dimanfaatkan untuk tanaman pangan, sedangkan perkebunan
banyak diusahakan pada lahan datar-bergelombang dengan lereng < 15%. Lahan
kering yang telah dimanfaatkan untuk perkebunan mencakup 19,60 juta ha (Badan
Pusat Statistik 2005), terutama untuk tanaman kelapa sawit, kelapa, dan karet.
3.
Ketersediaan air Pertanian
Keterbatasan
air pada lahan kering mengakibatkan usaha tani tidak dapat dilakukan sepanjang
tahun, dengan indeks pertanaman (IP) kurang dari 1,50. Penyebabnya antara lain
adalah distribusi dan pola hujan yang fluktuatif, baik secara spasial maupun
temporal. Wilayah barat lebih basah dibandingkan dengan wilayah timur, dan
secara temporal terdapat perbedaan distribusi hujan pada musim hujan dan
kemarau. Pada beberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, curah
hujan melebihi 2.000 mm/tahun, sehingga IP dapat ditingkatkan menjadi 2−2,50 (Las et al. 2000; Amien et al. 2001).
4.
Kepemilikan Lahan
Tantangan
yang lebih berat dan sukar diatasi adalah permasalahan sosial ekonomi,
antara
lain pemilikan lahan oleh petani cenderung menyempit . Data sensus pertanian tahun 1993 dan 2003,
serta hasil penelitian Puslitbangtanak pada tahun 2002/2003 (Abdurachman et al. 2005) menunjukkan luas lahan pertanian
di Jawa cenderung menurun, sedangkan di luar Jawa sedikit meningkat. Di lain
pihak, jumlah rumah tangga petani (RTP) meningkat secara signifikan dari 22,40
juta menjadi 27,40 juta dalam 10 tahun terakhir. Luas penguasaan lahan
rata-rata nasional menurun dari 0,86 ha menjadi 0,73 ha per RTP. Sejalan dengan
itu, jumlah petani gurem (luas lahan garapan < 0,50 ha) meningkat dari 10,80
juta RTP pada tahun 1993 menjadi 13,70 juta pada tahun 2003, atau rata-rata
meningkat 2,40%/tahun. Bila luas lahan pertanian tidak bertambah secara
signifikan seiring dengan laju pertambahan penduduk mak jumlah petani gurem
akan makin bertambah dan peluang perambahan hutan meningkat.
5.
Penggunaan dan Ketersediaan Lahan
Menurut
Badan Pusat Statistik (2005), lahan pertanian Indonesia meliputi 70,20 juta ha, sekitar 61,53 juta ha di antaranya
berupa lahan kering (Tabel 2) dengan produktivitas relatif rendah, jauh di
bawah potensi hasil. Produktivitas padi gogo berkisar antara 2−3 t/ha, padahal
potensinya dapat mencapai 4−5 t/ha (Sumarno dan Hidayat 2007). Demikian juga
komoditas
lain,
seperti kedelai, masih dapat ditingkatkan. Menurut Subandi (2007), peluang
peningkatan produktivitas kedelai masih terbuka, karena hasil di tingkat petani
(0,60−2 t/ha) masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan hasil di tingkat
penelitian, yang berkisar antara 1,70−3,20 t/ha. Selain meningkatkan
produktivitas lahan kering yang sudah ada (existing), produksi bahan pangan
dapat pula ditingkatkan melalui perluasan areal tanam pada lahan kering. Dari
76,22 juta ha lahan kering yang sesuai untuk pertanian (Tabel 1), lahan yang
telah digunakan (tegalan,
perkebunan,
kayu-kayuan, dan pekarang.
STRATEGI PENGELOLAAN
LAHAN KERING
Menurut Abdurachman
(2008), strategi yang dapat diterapkan untuk mengelola lahan kering agar dapat
bermanfaat bagi lahan pertanian antara lain sebagai berikut :
1.
Identifikasi Lahan Yang Sesuai
Cara
yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi lahan yang sesuai untuk pertanian,
terutama lahan alang-alang dan semak belukar adalah dengan menggunak a n peta pada penggunaan skala 1 : 250000 yang ditumpang tempatkan dengan peta arahan
tata ruang pertanian. Dengan cara ini, diperoleh data tentang lahan kering
cadangan seluas 22,39 juta ha, yang terdiri atas 7,08 juta ha sesuai untuk
tanaman pangan semusim dan 15,31juta ha untuk tanaman tahunan. Untuk memperoleh
data yang lebih tepat, harus digunakan peta tanah atau peta kesesuaian dan peta
penggunaan lahan dengan skala yang lebih besar, misalnya 1:50.000 atau lebih
baik lagi skala 1:25.000. Selain itu, data biofisik lahan perlu ditunjang
dengan informasi sosialekonomi, terutama status kepemilikan lahan, sehingga
pengembangan pertanian tidak terbentur pada permasalahan nonteknis, yang dapat
menggagalkan pendayaguna an lahan ke r
ing yang telah direncanakan.
2.
Seleksi Teknologi Tepat Guna
Teknologi
pengelolaan lahan kering untuk pertanian tanaman pangan telah tersedia, baik
teknologi konservasi tanah, peningka t an ke subur an t anah,
penge lol a an bahan organik tanah, dan
pengelolaan air. Dari sekumpulan teknologi tersebut, perlu di s e l eks
i t eknologi yang t
epa t guna , sesuai dengan kondisi lahan
(tanah, air, dan iklim) dan petani. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih
dulu karakteristik lahan dan kondisi petani agar teknologi yang terpilih
betul-betul efektif dan dapat diadopsi petani. Karakteristik lahan dapat
diketahui melalui pemetaan skala detail (1:50.000 atau 1:25.000), atau lebih
detail, skala 1:10.000 atau 1:5.000. Dengan menggunakan peta dengan skala
sangat detail, pemilihan komoditas dan teknologi dapat dilakukan dengan lebih
tepat. Aspek sosial-ekonomi petani dapat diketahui dengan melaksanakan survei
lapangan, misalnya dengan menggunakan metode Participatory Rural Appraisal
(PRA).
3.
Diseminasi Teknologi
Diseminasi
dan adopsi teknologi pada umumnya berjalan lambat, termasuk teknologi
pengelolaan lahan (tanah, air, dan iklim). Teknologi tersebut disebarkan
melalui seminar, simposium, jurnal, serta media cetak dan elektronik. Namun
akses penyuluh apalagi petani ke media tersebut relatif terbatas, sehingga cara
dan media penyampaian tersebut kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan
metode diseminasi secara langsung kepada petani, yang lebih mendekatkan sumber
teknologi dengan petani sebagai calon pengguna teknologi. Salah satu terobosan
dalam diseminasi teknologi pertanian adalah melalui Prima Tani (Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2006), yang bertujuan untuk mempe r c epa
t di s emina s i dan
adops I teknologi inovatif, terutama yang dihasilkan Badan Litbang
Pertanian. Melalui program ini, pertanian lahan kering, termasuk pengembangan
budi daya padi gogo, palawija dan sebagainya, misalnya dengan introduksi benih
unggul, pemupukan, dan rotasi tanaman, dapat
be
rkembang l ebih c epa t
dan mampu meningkatkan produksi bahan pangan nasional secara signifikan.
4.
Peningkatan Penelitian Pertanian Lahan
Kering
Penelitian
padi saat ini lebih terfokus pada padi sawah, yang telah menghasilkan
berbagai
varietas unggul dan teknologi budi daya seperti pengendalian hama/ penyakit,
pemupukan, dan pengairan. Penelitian dan pengembangan padi gogo jauh
tertinggal. Sejalan dengan itu, minat
dan upaya petani untuk mengembangkan padi gogo juga relatif rendah, tercermin
dari luas pertanaman setiap tahun yang jauh lebih rendah dari luas lahan sawah.
Ke
depan, penelitian dan pengembangan pe r t ani an l ahan ke r ing pe r lu mendapat perhatian
yang lebih besar, termasuk pembiayaannya. Akan lebih baik bila penelitian
diarahkan pada teknologi penge lol a an padi
gogo dan pa l awi j a sebagai bagian dari sistem usaha tani
(farming
system) yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi. Penelitian hendaknya
dilaksanakan secara komprehensif, dalam arti peneliti tidak bekerja
sendiri-sendiri, tetapi dalam suatu tim dari berbagai disiplin ilmu, sehingga
dapat menghasilkan teknologi yang efektif dan menguntungkan.
DAFTAR PUSTAKA
Abdurachman, A., Dariah, A., dan Mulyani, A. 2008. Strategi dan teknologi pengelolaan lahan
kering mendukung pengadaan pangan nasional. Jurnal Litbang Pertanian 27 (2)
: 43-49.